
Oleh AMIN R ISKANDAR
DALAM bahasa Indonesia, terma literary journalism bisa diartikan jurnalistik sastra. Praktiknya, jurnalistik sastra bukan berarti karya tulis yang membahas mengenai sastra. Tapi sebuah style pelaporan peristiwa (berita) yang mirip karya sastra. Bedanya adalah produk literary journalism bersifat faktual bukan fiktif; seperti cerpen dan novel. Oleh karena itu, kalangan jurnalis menyebutnya dengan istilah new journalism, jurnalistik (gaya) baru.
Satu hal yang menjadi daya tarik dari literary journalism adalah terletak dalam elaborasi dua entitas (keterampilan) yang berbeda, yakni (keterampilan) jurnalistik dan sastra. Jurnalistik di satu sisi, merupakan keterapilan mencari, mengungkap, mengklasifikasi, menulis, mengedit dan mempublikasikan fakta di media massa. Di sisi lain, sastra menawarkan sebuah style tulisan dengan kekuatan imajinative description, detil, membangkitkan human interest, dan bahasa yang lentur, santun, halus, renyah dibaca bahkan sesekali bergaya puitik.
Alhasil pertautan antara jurnalistik dan sastra akan menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang exelence. Karya yang selain memiliki unsur keakuratan data dan fakta, enak dibaca, juga tajam dalam menyentuh sense pembaca. Sayang, untuk di Indonesia karya ini cukup langka, sulit ditemukan. Sepertinya hanya tempo dari sekian banyak majalah yang biasa menyajikan karya literary journalism dengan baik. Untuk harian umum, Kompas juga mulai sedikit bergaya magajin. Padahal banyak jurnalis sekaligus sastrawan yang kiranya dapat dijadikan “guru”. Sebut saja Rosihan Anwar, Goenawan Mohamad, Mochtar Lubis, Seno Guira Ajidarma, Isma Sawitri, dan Budiman S. Hartoyo.
Untuk konteks kekinian, bila para jurnalis mau sedikit jeli, tekun, dan sabar dalam proses refortase, sesungguhnya banyak hal yang menarik untuk disajikan dengan gaya sastra. Seperti perubahan perilaku caleg yang kalah dalam pemilihan, eksotisme alam yang kian hari kian memudar, pelaku industri kreatif dengan pasilitas manual, dan yang paling menarik adalah peristiwa gangguan jiwa massal di kecamatan Kersamanah, kabupaten Garut, Jawa Barat.
Berita mengenai fenomena gangguan jiwa masyarakat kecamatan Kersamanah, alangkah lebih “bersuara” jika berita dikemas dengan gaya sastra. Artinya reforter (wartawan) menarasikan seluruh peristiwa yang terjadi. Dari mulai aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari, mula-mula munculnya gejala kejiwaan, sebab-sebabnya, perubahan perilaku individu, sampai puncaknya masyarakat benar-benar mengalami kegilaan.
Cerita nyata
Bentuk literary journalism lebih tepat bila dikategorikan sebagai cerita (baca: kisah) nyata. Cerita yang kecil kemungkinan mengandung kebohongan. Tapi status literary journalism tidak setingkat dengan karya sastra realis. Hanya terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kesamaannya terletak dalam rujukan peristiwa, data, dan fakta. Bedanya, literary journalism “mengharamkan” bumbu nilai-nilai fiktif. Sedangkan sastra realis begitu kental dengan muatan-muatan fiktif sebagai bumbu cerita.
Untuk ranah Jawa Barat yang lebih terkenal dengan budaya tutur daripada budaya baca. Literary journalism akan efektif sebagai jembatan agar masyarakat lebih melek aksara. Karena literary journalism (kurang lebih) bergaya tutur. Selain menyajikan cerita, literary journalism dilengkapi dengan bahasa yang variatif, santai, ringan, dan dibantu dengan imajinasi yang menempatkan pembaca seolah-olah berada di lokasi kejadian. Dalam arti lain, pembaca diajak berkelana ke suatu tempat dan di sana bertemu dengan banyak orang.
Permasalahannya adalah apakah hal ini dapat diwujudkan di Jawa Barat? Jawabannya tentu saja bisa. Sebab, Jawa Barat memiliki segudang sastrawan yang dapat digali ilmunya oleh para wartawan. Seperti Acep Zamzam Noor, Hawe Setiawan, Usep Romli HM, Ajip Rosidi, Soni Farid Maulana dan yang lainnya. Setidaknya belajar bagaimana menulis dengan gaya cerita pendek dan novel.
Posisi satra
Seno Gumira Ajidarma mengungkapkan “ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara.” Artinya sastra boleh diandalkan sebagai senjata alternatif industri pers ketika posisinya ditekan. Kondisi ini sering dialami oleh pers yang menganut outoriterian pers system, yang pernah dialami oleh pers Indonesia pada orde baru.
Namun kondisi jurnalisme yang bebas bukan berarti sastra tidak berhak untuk bicara. Justru dalam kebebasan pers kali ini sastra tetap harus bicara. Bahkan patut lebih kreatif lagi. Gunanya agar pers tidak kehilangan pijakan lantas beralih ke jalan kebablasan. Kebablasan pers secara fundamental dapat ditilai melalui bahasa yang digunakan si wartawan. Karena kekuatan pers sangat ditentukan oleh kekuatan bahasa. Dalam hal ini, sastra memiliki cara yang jitu dalam menyaring bahasa yang tepat dan tetap santun.
Beda halnya dengan Goenawan Mohammad yang dalam buku “Sastra dan Kekuasaa” menyatakan “pada awalnya, sastra adalah komunikasi.” Jika benar demikian, maka sastra dan jurnalistik kedudukannya sama-sama di bawah rumpun komunikasi. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan lagi.
Akhirnya patut untuk mulai bertanya, niatkah kita megindahkan gaya literary journalism dalam lembaran media massa? Jawabannya tentu saja diserahkan pada institusi media massa yang ada.



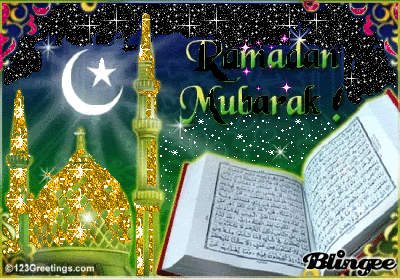
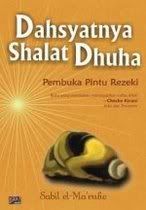
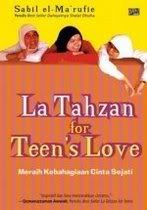
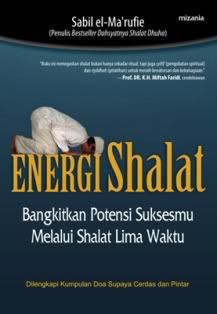

0 komentar:
Posting Komentar